
The Bumi Panua has Fallen : Sebuah Renungan di Balik Tragedi

Jejak Kedamaian yang Retak dan Hukum yang Timpang
Berita Baru, Tajuk, Hari ini, 21 September 2023 terjadi sebuah tragedi melintasi sejarah pesisir Gorontalo, yang pernah disebut sebagai “Serambi Madinah” dan diakui sebagai daerah adat oleh VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Gorontalo, dengan pesona alamnya yang memukau dan warisan budayanya yang kaya, terutama Kabupaten Pohuwato, telah lama menjadi lambang kedamaian dan keindahan. Namun, kini senyum yang dulu menghiasi daerah ini perlahan memudar, dan impian damainya retak oleh realitas yang pahit tentang jatuhnya bagian dari Serambi Madinah, yang dahulu begitu megah dan damai, tetapi kini telah berubah menjadi kisah dengan kepedihan yang mendalam. padahal di tanah ini, leluhur Gorontalo menanamkan akarnya dengan penuh semangat spiritual berlandaskan semboyan “Aadati Hulo-huloA to Syara’a, Syara’a Hulo-HuloA to Kitabullah,” berjuang untuk masa depan Gorontalo yang lebih baik.
Dari setiap sudut padang, keheningan yang pernah memeluk Gorontalo telah tergantikan oleh dentuman api yang meledak diiringi kemarahan. Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato terbakar, Kantor DPRD dirusak, sementara beberapa Gedung semi permanen dan properti milik perusahaan pertambangan serta pemerintah yang beroperasi di kabupaten pohuwato hancur terperosok oleh amarah yang membakar sebagian masyarakat. Kedamaian telah meredup, seperti matahari yang tenggelam di ufuk timur. Penghancuran bukan hanya fisik, melainkan perumpamaan dari keretakan yang tak terlihat antara hubungan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat, yang dulu bersatu dalam kehangatan dan warisan budaya, kini terpecah oleh kemarahan dan kebingungan. Hukum dan mediasi, yang dulu menjadi jalan untuk penyelesaian-pun, telah ditinggalkan begitu saja.
Lalu menjadi pertanyaan besar sebagai negara demokratis “mengapa langkah konkrit dari mediasi ini kemudian ditanggalkan dan lebih memilih tindakan anarkis dalam pemikiran masyarakat?”. Merujuk pada pasal 8 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral Dan Batubara (UU MINERBA) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil. Apakah pemerintah gagal dalam melakukan mediasi? atau justru mediasinya tidak mampu menciptakan “equality” antara Pihak perusahaan dan masyarakat?
Apabila menggunakan kacamata hukum maka jelas bahwa tidak ada satupun aturan yang secara detail ataupun secara “lex specialis” melindungi aktivitas penambang yang tidak memiliki izin yang sah. sebab di dalam UU MINERBA dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP TPKU MINERBA) serta peraturan terkait lainnya, hanya mengatur terkait dengan biaya ganti rugi perselisihan antara perusahaan dan masyarakat dalam beberapa persoalan di antara yakni masyarakat yang berdampak negatif secara langsung contohnya; seperti pencemaran air dan udara, serta merusak lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat, yang berikut terkait dengan Dampak lingkungan dan kecelakaan kerja yang melibatkan masyarakat. Adapun dalam persoalan perebutan wilayah pertambangan yang berpotensi untuk diberikan Hak Guna dan perlindungan atas masyarakat-nya hanya terbatas pada kategori hutan adat yang masyarakatnya hidup dan masih diakui. hal ini diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah turunan lainnya.
Disisi lain hutan yang menjadi pokok perselisihan antara masyarakat dan perusahaan di kabupaten Pohuwato tidak memenuhi unsur-unsur diatas, selain itu masyarakat penambang pun tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan). sehingga bila ditarik benang merahnya, masyarakat penambang tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk menghadapi persoalan ini, apalagi harus meminta keadilan dengan jalur hukum. oleh sebab itu, langkah mediasi dalam persoalan ini dipandang sebagai “ultimum remedium” atau upaya terakhir menyelesaikan pokok masalah perselisihan pertamabang di kabupaten pohuwato. Tidak boleh dipandang sebelah mata!
Lantas apakah kita harus menyalahkan perusahaan dalam hal ini? tentu tidak juga, karena perusahaan hanyalah bentuk badan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang legal secara hukum, mereka adalah sekumpulan orang yang sama mampu melihat nilai komersial di dunia usaha pertambangan. kacamata yang digunakan adalah kacamata bisnis, yang itu artinya apabila mereka telah menempuh upaya dan jalur hukum sesuai prosedur maka tidak satu hal pun yang memberatkan mereka untuk melakukan aktivitas produksi untuk mencari keuntungan, layaknya setiap manusia yang memiliki hak dan kewajiban, selama tidak melanggar hukum yang berlaku.
Penulis tidak mampu membayangkan bagaimana rumitnya pengurusan izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dilalui oleh setiap perusahaan pertambangan salah satunya perusahaan tambang yang ada di pohuwato. dimulai dari mengajukan permohonan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), kemudian IUP eksplorasi, lalu IUP Produksi dan seterusnya tentulah tidak mudah, penulis meyakini bahwa besaran modal awal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tentu sudah sangat fantastis.
Kemudian menjadi pertanyaan berikutnya “dari mana legalitas yang dimiliki oleh perusahaan?”, “bagaimana cara pengurusannya?”. apabila merujuk pada UU MINERBA maka segala bentuk pengurusan izin pertambangan yakni dibawah naungan Kementrian ESDM yang lebih lanjut “dimandori” oleh Inspektur Pertambangan dan Pemerintah Wilayah Provinsi sebagai keterwakilan pemerintah pusat didaerah. lalu bagaimana dengan pemerintah kabupaten? inilah yang kemudian begitu menyesakkan, sebab pemerintah kabupaten dalam hal ini tidak memiliki “mahkota kewenangan” sama halnya dengan pemerintah pusat dan provinsi pada wilayah administrasi pertambangan. dengan kata lain pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun terkait aktivitas pertambangan oleh perusahaan. satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah hanyalah koordinasi dan mediasi dengan perusahaan, pemerintah pusat dan provinsi.
Terlepas dari rumitnya persoalan kewenangan di bidang pertambangan, bila melihat sudut pandang psikologis masyarakat penambang apa terjadi hari ini tentu sulit untuk memenuhi rasa keadilan. karena tidak ada keuntungan “secara langsung” yang dapat mereka rasakan ketika mereka menyerahkan kekayaan alam yang mereka kelola dan dijadikan sebagai sandaran serta penopang ekonomi keluarga yang tidak lain dipercayai adalah warisan dari nenek moyangnya kepada perusahaan dengan biaya ganti rugi yang kecil. itupun menggunakan frasa “tali asih” bukan ganti rugi dengan perbandingan pembayaran dan pendapatan dari tambang 1:1000. belum lagi persoalan jumlah penambang yang berkisar dua ribuan, tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada perekonomian daerah. dimana nanti masyarakat akan mencari nafkah? menjalankan kehidupan sesuai dengan interprestasi tujuan penciptaan manusia. Sangatlah tidak mengheran ketika mediasi tidak memenuhi “ekspektasi dari masyarakat penambang dan menemui “Stalemate” atau jalan buntu, maka tindakan anarkis menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh masyarakat penambang.
Tragedi 21 September 2023 ini begitu pelik dan tidak pernah terbesit akan berakhir dengan memilukan seperti hari ini. para pendemo hari ini mau tidak mau, suka tidak suka harus menjalani proses hukum, karena telah melakukan perusakan terhadap fasilitas negara, walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh pendemo hari ini adalah bentuk kemarahan atas kebijakan dan ketidakpuasan atas hasil mediasi yang secara “batiniyah” tentu sangat dipahami!. Namun, seperti adagium hukum “Lex dura, sed tamen scripta” yang artinya “hukum memang kejam, tetapi begitulah bunyinya”.
Menelaah Mitos dan Realitas Kepemimpinan dalam Konteks Tragedi Pertambangan
Hari ini, di tengah banyaknya desas-desus seputar tragedi perselisihan pertambangan, muncul satu pertanyaan yang menarik perhatian penulis. Pertanyaan ini, yang menurut penulis terkesan sarkastik, datang dari kalangan masyarakat biasa, yaitu, “ma uwitolo yio jangan salah ba pilih (memilih) pemimpin………..” Penulis merasa bahwa pernyataan ini sering terdengar, namun dari pernyataan ini tiba-tiba muncul pertanyaan yang mengganggu, yaitu, apakah semua ini adalah cerminan dari kegagalan sosok pemimpin yang selalu mengakar pada kultur “Uduluwo Lo Ulimo Lo PohalaA”?, atau apakah kemarahan ini adalah bentuk sumpah serapah yang pernah dikumandangkan oleh para leluhur pada 12 Sya’ban 1084 Hijriah;
“Dan jikalau tiada kehendak negeri, hanya kehendak raja sendiri atau Huhuhu atau kehendak Wuleya lo Lipu atau kehendak anak-anak raja atau kehendak orang-orang besar, maka yang punya kehendak atau perbuatan itu luluh lantak menjadi laksana kapur dan hancur lebur bagai lemak kerbau yang dipersembahkan itu.”
Sumpah itu ditutup dengan kalimat “Dan barang siapa yang mengubah perjanjian itu, negeri Limboto atau negeri Gorontalo, menjadi kafir na’udzubillahi minhaa finnaari jahannama dan negerinya binasa laksana laut atau kapur atau menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu…. dst… Innallaaha tukhliful mii’aad…dst… Wallaahi, Billaahi, Tallaahi.” (Medi Botutihe: “Mo’odelo”)
Bilamana benar demikian maka Naudzubillah Min Zalik. penulis tidak ingin memberi rasa takut kepada siapapun, akan tetapi walaupun perkataan ini adalah mitos yang sering dipandang sebagai “superstitious” namun banyak kesempatan semua telah menyaksikan bukti dari berbagai “balla” akan selalu datang bersamaan dengan kepemimpinan yang “Zalim”. Bencana yang dimaksudkan tidak hanya terpaku pada bencana alam akan tetapi perpecahan, fitnah dan kehancuran pun termasuk didalamnya
Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang seharusnya disalahkan atas kejadian ini? Apakah pemimpin di tingkat kabupaten, provinsi, atau bahkan pemimpin di tingkat pusat, seperti Presiden dan Kementerian ESDM? Tentu, ini tidak semudah meletakkan kesalahan pada satu individu atau kelembagaan saja. perumpamaannya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, ini bukan kisah hitam dan putih yang sederhana. Lebih tepatnya, ini adalah gambaran yang kaya dan kompleks. seperti halnya sebuah palet warna seorang seniman yang terdiri dari banyak unsur untuk menciptakan sebuah karya seni, begitupula dalam tragedi ini tentu semuanya berkontribusi!.
Mari bersama-sama melakukan evaluasi mendalam terhadap langkah-langkah yang telah diambil selama ini benar-benar untuk membangun atau justru saling melukai satu sama lain “Wallahi-wallahi otutu, Hulontalo Limutu, U tutuwawuwo otutu, Dahai Bolo Moputu, Ode janji to buku”. Hari ini, semuanya harus menerima dengan lapang dada kenyataan pahit bahwa Pohuwato harus memulai semuanya dari awal. Ibarat pepatah yang mengatakan “from zero to hero”, kini kita menghadapi situasi yang sebaliknya, “from hero to zero”. Fokus kita bukan lagi tentang siapa yang salah atau siapa yang kalah, perumpamaannya ibarat antara kaca spion mobil dan kaca depan mobil, kaca spion diciptakan begitu kecil sebab fokus utama kita bukan di kaca spion atau masa yang telah lewat melainkan kaca depan, sebab itulah kaca depan bentuknya lebar agar kita bisa dengan jelas melihat jauh kedepan, seperti itu pula penempatan fokus kita dalam persoalan ini. Fokusnya adalah bagaimana menata kembali, tidak hanya perkara infrastruktur, tetapi juga dalam memperkuat ikatan kasih sayang antara semua pihak untuk merestorasi kedamaian yang telah diagung-agungkan oleh para tetua Gorontalo di masa lalu. penulis teringat sebuah catatan diskusi oleh (Ranyansyah R).
“Bangsa ini….. negeri ini kita yang hiasi, kita satu dalam nasib, dalam aksi, ketika
kelaparan kita berbagi nasi ,saling menopang menggapai visi. Hanyut saling menolong, jatuh saling menegakan. naik tanpa menurunkan orang lain, maju tanpa memundurkan orang lain, baik tanpa menggagalkan orang lain, hidup tanpa mematikan orang lain. merangkak, berjalan, berlari, hingga mendaki bersama. perempuan seharusnya tidak lagi menjadi objek penipuan, laki laki tidak lagi menjadi objek luka-luka, manusia tak lagi menjadi makhluk sia sia. budaya menjadikan kita berdaya, adat menjadikan kita lebih beradab.”
Pada akhirnya, tragedi yang terjadi pada 21 September 2023 ini menjadi pukulan keras dan “reminder” bagi kita semua bahwa segala tindakan yang kita lakukan akan selalu tunduk pada hukum kausalitas (sebab-akibat). Oleh karena itu, catatan penting yang harus diambil dari hari ini adalah bahwa di masa depan, semua yang kita lakukan, baik itu dimulai dari tingkat individu hingga ke tingkat lembaga, harus mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya secara vertikal tetapi juga secara horizontal.
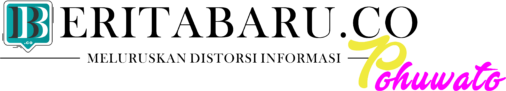

 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co Gubuktulis.com
Gubuktulis.com surau.co
surau.co




